 Teknologi bukan lagi sekadar alat bantu—ia telah merasuk menjadi nadi kehidupan modern. Setiap pagi, jutaan orang di dunia, termasuk Indonesia, dibangunkan bukan oleh suara bel mekanik, melainkan oleh getar smartphone yang terhubung dengan jadwal kalender digital. Sambil menyesap kopi, kita mengecek notifikasi: pesan dari keluarga di luar kota, update berita terkini, atau bahkan peringatan cuaca ekstrem dari aplikasi BMKG. Perjalanan ke kantor dimulai dengan membuka aplikasi navigasi seperti Google Maps yang secara real-time menghindari kemacetan, sambil GoPay atau OVO memudahkan pembayaran parkir elektronik di mal. Di kantor, email, platform kolaborasi seperti Slack, dan software manajemen proyek menjadi teman setia. Pulang kerja, kita memesan makanan via GrabFood atau Foodpanda, menonton serial di Netflix atau Disney+, lalu tertidur dengan musik dari Spotify. Ini bukan skenario fiksi—ini realitas hidup di era digital, di mana teknologi bukan pilihan, melainkan kebutuhan primer yang membentuk cara kita berpikir, bekerja, bersosialisasi, dan memaknai dunia.
Teknologi bukan lagi sekadar alat bantu—ia telah merasuk menjadi nadi kehidupan modern. Setiap pagi, jutaan orang di dunia, termasuk Indonesia, dibangunkan bukan oleh suara bel mekanik, melainkan oleh getar smartphone yang terhubung dengan jadwal kalender digital. Sambil menyesap kopi, kita mengecek notifikasi: pesan dari keluarga di luar kota, update berita terkini, atau bahkan peringatan cuaca ekstrem dari aplikasi BMKG. Perjalanan ke kantor dimulai dengan membuka aplikasi navigasi seperti Google Maps yang secara real-time menghindari kemacetan, sambil GoPay atau OVO memudahkan pembayaran parkir elektronik di mal. Di kantor, email, platform kolaborasi seperti Slack, dan software manajemen proyek menjadi teman setia. Pulang kerja, kita memesan makanan via GrabFood atau Foodpanda, menonton serial di Netflix atau Disney+, lalu tertidur dengan musik dari Spotify. Ini bukan skenario fiksi—ini realitas hidup di era digital, di mana teknologi bukan pilihan, melainkan kebutuhan primer yang membentuk cara kita berpikir, bekerja, bersosialisasi, dan memaknai dunia.
Table of Contents
- Kecerdasan Buatan: Otak Tak Terlihat di Balik Layar
- Internet of Things (IoT): Ketika Benda Bisa "Bicara"
- 5G: Jalan Tol Informasi untuk Masa Depan
- Blockchain: Lebih dari Sekadar Mata Uang Kripto
- AR/VR: Menyatu dengan Dunia Digital
- Teknologi Hijau: Solusi untuk Bumi yang Terancam
- Dunia Kerja Baru: Antara Peluang dan Kecemasan
- Menghadapi Masa Depan: Menjadi Pilot, Bukan Penumpang
- Teknologi Wearable: Ekosistem Kesehatan di Pergelangan Tangan
- Edge Computing: Otak Terdistribusi di Era IoT
- Keamanan Siber: Perang Bayangan di Ruang Digital
- Menjadi Arsitek Masa Depan di Tengah Badai Teknologi
Kecerdasan Buatan: Otak Tak Terlihat di Balik Layar
Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi mesin penggerak utama transformasi digital. Tapi apa sebenarnya AI itu? Sederhananya, AI adalah sistem komputer yang bisa meniru kemampuan belajar dan pemecahan masalah manusia. Bedanya, AI bisa memproses data dalam skala yang tak terbayangkan oleh otak manusia. Ambil contoh asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, atau Alexa. Ketika kamu berkata, "Hidupkan lampu ruang tamu," AI tidak hanya memahami perintah suara, tapi juga mengidentifikasi lokasi perangkat, mengenali pola suara unikmu, dan mengeksekusi perintah melalui jaringan IoT (Internet of Things). Di balik layar, AI menggunakan Natural Language Processing (NLP) untuk mengurai kalimat, Machine Learning (ML) untuk belajar dari interaksi sebelumnya, dan Deep Learning untuk meningkatkan akurasi.
Di Indonesia, AI mulai merambah berbagai sektor. Gojek, misalnya, menggunakan AI untuk mengoptimalkan rute pengemudi, memprediksi permintaan layanan, bahkan mendeteksi penipuan transaksi. Di bidang kesehatan, rumah sakit seperti Siloam memanfaatkan AI untuk menganalisis hasil CT scan guna mendeteksi dini tumor atau kelainan paru-paru dengan akurasi di atas 90%. Bahkan startup lokal seperti Alodokter mengandalkan AI chatbot untuk menjawab pertanyaan kesehatan dasar sebelum pasien terhubung ke dokter sungguhan. Tapi AI juga menimbulkan dilema: bagaimana dengan data pribadi yang dikumpulkan? Apakah algoritma bisa bersifat bias? Contoh nyata terjadi di AS, di mana algoritma perekrutan ternyata mendiskriminasi kandidat perempuan karena dilatih dengan data historis yang tidak seimbang. Di Indonesia, isu privasi data menjadi sorotan setelah kebocoran data jutaan pengguna e-commerce. AI adalah teknologi ganda: ia bisa menjadi pemberdaya atau pengawas, tergantung bagaimana kita mengatur dan menggunakannya.
Internet of Things (IoT): Ketika Benda Bisa "Bicara"
Bayangkan rumahmu yang pintar: saat kamu terbangun, gorden otomatis terbuka, mesin kopi menyala, dan suhu ruangan disesuaikan dengan cuaca di luar. Ini bukan film sci-fi—ini IoT dalam aksi. IoT mengacu pada jaringan perangkat fisik—dari kulkas hingga sepatu—yang dilengkapi sensor, perangkat lunak, dan konektivitas internet untuk mengumpulkan dan bertukar data. Di Jakarta, proyek "Smart City" mulai mengimplementasikan IoT untuk mengelola lalu lintas. Sensor di lampu merah mendeteksi volume kendaraan dan menyesuaikan durasi hijau secara otomatis, sementara tempat sampah pintar mengirim notifikasi ke petugas saat penuh. Di bidang pertanian, petani di Jawa Tengah menggunakan sensor kelembaban tanah yang terhubung ke aplikasi mobile untuk mengatur irigasi, menghemat air hingga 40%.
Tapi IoT juga membawa risiko besar. Setiap perangkat yang terhubung adalah potensi pintu masuk bagi peretas. Pada 2016, serangan siber terbesar dalam sejarah, Mirai Botnet, menyerang situs besar seperti Twitter dan Netflix dengan cara membajak kamera pengawas IoT yang tidak aman. Di Indonesia, kebocoran data CCTV pernah terjadi di beberapa kantor pemerintahan. Selain itu, masalah e-waste (limbah elektronik) muncul ketika perangkat IoT cepat usang dan sulit didaur ulang. IoT adalah teknologi yang mengubah benda mati menjadi "hidup", tapi tanpa keamanan dan regulasi yang ketat, ia bisa menjadi mata-mata diam di dalam rumah kita.
5G: Jalan Tol Informasi untuk Masa Depan
Jika 4G adalah jalan raya, maka 5G adalah jalan tol super cepat dengan 10 lajur. Teknologi generasi kelima ini bukan sekadar peningkatan kecepatan internet—ia adalah fondasi bagi revolusi berikutnya. Dengan latensi ultra-rendah (kurang dari 1 milidetik) dan kapasitas 100 kali lebih besar dari 4G, 5G memungkinkan konektivitas real-time untuk miliaran perangkat. Contoh paling nyata: mobil otonom. Untuk beroperasi aman, mobil self-driving perlu berkomunikasi dengan kendaraan lain, lalu lintas, dan infrastruktur dalam hitungan milidetik—hanya mungkin dengan 5G. Di bidang kesehatan, 5G mendukung operasi jarak jauh (telesurgery) di mana ahli bedah di Jakarta bisa mengendalikan robot pembedah di Papua dengan presisi tinggi.
Indonesia mulai menggelar 5G sejak 2021, dengan fokus di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. Tantangannya? Biaya infrastruktur yang mahal (membutuhkan lebih banyak base station karena frekuensi tinggi), keterbatasan spektrum, dan kesenjangan digital. Banyak daerah terpencil masih kesulitan akses 4G, apalagi 5G. Selain itu, ada kekhawatiran publik tentang radiasi 5G, meski WHO dan penelitian ilmiah menyatakan tidak ada bukti dampak kesehatan signifikan. 5G adalah kunci bagi Indonesia untuk bersaing di ekonomi digital, tapi tanpa distribusi merata dan edukasi publik, teknologi ini justru bisa memperlebar jurang digital.
Blockchain: Lebih dari Sekadar Mata Uang Kripto
Ketika mendengar "blockchain," kebanyakan orang langsung terpikir Bitcoin atau Ethereum. Padahal, teknologi ini memiliki potensi jauh lebih luas. Pada dasarnya, blockchain adalah database digital yang terdesentralisasi, tidak bisa diubah, dan transparan. Setiap transaksi dicatat sebagai "blok" yang terhubung secara kriptografis, menciptakan rantai data aman tanpa perantara. Di Indonesia, blockchain mulai digunakan untuk:
- Rantai Pasokan:
Perusahaan seperti Unilever melacak produk dari pabrik hingga ke rak minimarket menggunakan blockchain, memastikan keaslian dan mengurangi pemalsuan.
- Pemilu:
Pilpres 2024 diuji coba dengan sistem voting berbasis blockchain di beberapa TPS untuk mencegah kecurangan.
- Kepemilikan Aset:
Platform seperti TokoMall memungkinkan pembelian properti atau emas dengan token blockchain, memudahkan investasi fraksional.
Tapi blockchain bukan tanpa kontroversi. Konsumsi energinya yang tinggi (terutama untuk mekanisme Proof of Work) berdampak pada lingkungan. Selain itu, sifatnya yang anonim juga disalahgunakan untuk pencucian uang atau transaksi ilegal. Regulasi di Indonesia masih ketat—OJK hanya mengizinkan 13 aset kripto untuk diperdagangkan, sementara blockchain di sektor keuangan diawasi ketat oleh Bank Indonesia. Blockchain adalah teknologi revolusioner yang bisa mendemokratisasi kepercayaan, tapi hanya jika diatur dengan bijak.
AR/VR: Menyatu dengan Dunia Digital
Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) sedang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. AR menumpangkan elemen digital ke dunia nyata (misalnya filter Instagram yang menambahkan kucing di kepalamu), sementara VR menciptakan lingkungan imersif sepenuhnya (seperti bermain game dengan headset Oculus). Di Indonesia, AR/VR mulai diadopsi di berbagai sektor:
- Pendidikan:
Universitas Indonesia menggunakan VR untuk simulasi bedah medis, memungkinkan mahasiswa kedokteran berlatih tanpa risiko.
- Pariwisata:
Candi Borobudur bisa "dikunjungi" secara virtual melalui aplikasi Borobudur AR, lengkap dengan penjelasan sejarah interaktif.
- Retail:
Brand seperti Erha memanfaatkan AR untuk "coba" produk skincare secara virtual sebelum membeli.
Tapi adopsi massal masih dihadang hambatan: perangkat VR masih mahal (seperti Apple Vision Pro seharga Rp 50 jutaan), ukuran yang besar, dan masalah kenyamanan (mabuk gerak). Selain itu, ada kekhawatiran soal privasi—kamera AR terus-menerus merekam lingkungan sekitar. AR/VR menjanjikan pengalaman tanpa batas, tapi teknologi ini masih dalam tahap awal perjalanannya.
Teknologi Hijau: Solusi untuk Bumi yang Terancam
Di tengah krisis iklim, teknologi menjadi harapan terakhir. Inovasi dalam teknologi hijau (green tech) fokus pada solusi berkelanjutan:
- Energi Terbarukan:
Panel surya generasi baru (perovskite) 30% lebih efisien dan 5 kali lebih murah dari teknologi lama. Di Indonesia, PLN sedang mengembangkan floating solar farm di Waduk Cirata, terbesar di Asia Tenggara.
- Pertanian Cerdas:
Drone dan sensor IoT digunakan untuk memantau kesehatan tanaman, mengurangi penggunaan pestisida hingga 50%. Startup seperti TaniHub menghubungkan petani langsung dengan pembeli, memangkas rantai pasokan.
- Daur Ulang Limbah:
Teknologi pirolisis mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, sementara startup seperti Replas mengubah limbah menjadi bahan bangunan.
Tapi transisi ke teknologi hijau tidak mudah. Infrastruktur energi fosil masih dominan—85% energi Indonesia berasal dari batu bara. Selain itu, ekstraksi mineral untuk baterai listrik (lithium, kobalt) seringkali merusak lingkungan dan melanggar HAM. Teknologi hijau hanya efektif jika didukung kebijakan yang tegas dan kesadaran publik.
Dunia Kerja Baru: Antara Peluang dan Kecemasan
Teknologi sedang merekonfigurasi lapangan kerja secara drastis. Otomatisasi menggantikan pekerjaan rutin: kasir diganti oleh self-checkout, staf administrasi oleh software RPA (Robotic Process Automation), bahkan jurnalis bisa dibantu AI untuk menulis laporan data. Di sisi lain, teknologi menciptakan profesi baru: data scientist, AI trainer, drone pilot, hingga prompt engineer (ahli perintah AI). Fenomena kerja jarak jauh (remote work) yang meledak selama pandemi menunjukkan bahwa banyak pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja—asalkan ada konektivitas. Platform seperti LinkedIn dan Glints melaporkan peningkatan lowongan kerja digital di Indonesia hingga 40% sejak 2020.
Tapi perubahan ini menimbulkan ketegangan. Menurut World Bank, 23 juta pekerja di Indonesia berisiko tergantikan otomatisasi dalam 10 tahun. Kesenjangan digital antara yang melek teknologi dan tidak juga memperlebar ketimpangan. Di sisi lain, kerja jarak jauh menimbulkan masalah baru: kelelahan digital (burnout), kesulitan membangun budaya perusahaan, dan isolasi sosial. Pendidikan dan pelatihan ulang (reskilling) menjadi kunci. Pemerintah Indonesia meluncurkan program Prakerja untuk melatih masyarakat dalam keterampilan digital, tapi masih jauh dari cukup. Dunia kerja masa depan membutuhkan fleksibilitas dan pembelajaran seumur hidup—siapa yang tidak beradaptasi, akan tertinggal.
Menghadapi Masa Depan: Menjadi Pilot, Bukan Penumpang
Revolusi teknologi yang kita alami hari ini seperti banjir bandang: tak bisa dihentikan, tapi bisa diarahkan. Optimisme buta yang menganggap teknologi sebagai obat semua masalah sama berbahayanya dengan pesimisme yang menolak perubahan. Teknologi adalah alat—dampaknya tergantung pada siapa yang mengendalikannya. AI bisa meningkatkan produktivitas atau memperkuat bias sistemik. IoT bisa menciptakan kota berkelanjutan atau sistem pengawasan massal. Blockchain bisa mendemokratisasi keuangan atau memfasilitasi kejahatan. Pilihan ada di tangan kita.
Untuk memastikan teknologi berdampak positif, kita butuh tiga pilar:
- Inovasi Bertanggung Jawab:
Pengembang teknologi harus mempertimbangkan implikasi etis sejak tahap desain. Contoh: DeepMind (milik Google) membentuk dewan etika untuk mengawasi pengembangan AI.
- Regulasi Adaptif:
Pemerintah perlu membuat aturan yang melindungi hak-hak individu tanpa menekan inovasi. Indonesia sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), tapi implementasinya masih lemah.
- Literasi Digital Merata:
Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami teknologi, bukan hanya menjadi konsumen pasif. Program seperti "Digital Talent Scholarship" dari Kominfo adalah langkah baik, tapi perlu diperluas
Teknologi akan terus berkembang—dari metaverse hingga quantum computing—dengan kecepatan yang mengejutkan. Yang bisa kita lakukan adalah bersiap: terus belajar, kritis terhadap informasi, dan aktif membentuk arah perubahan. Di era di mana kode pemrograman bisa lebih berkuasa dari undang-undang, menjadi pilot teknologi bukan pilihan—melainkan keharusan. Masa depan bukan sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang diciptakan. Dan teknologi adalah palu godoknya.
Teknologi Wearable: Ekosistem Kesehatan di Pergelangan Tangan
Teknologi wearable telah berevolusi dari sekadar fitness tracker menjadi sistem pemantau kesehatan personal yang canggih. Smartwatch seperti Apple Watch Series 9 atau Samsung Galaxy Watch6 kini dilengkapi sensor EKG, deteksi sleep apnea, dan analisis oksigen darah (SpO2) dengan akurasi medis. Di Indonesia, Halodoc bekerja sama dengan Samsung untuk mengintegrasikan data wearable ke platform telemedicine, memungkinkan dokter memantau pasien kronis seperti diabetes atau hipertensi secara real-time. Bahkan inovasi lebih jauh: perusahaan startup lokal Nusantics mengembangkan "smart ring" yang menganalisis kualitas tidur dan tingkat stres melalui sensor PPG (Photoplethysmography).
Namun, tantangan etika muncul: Siapa pemilik data kesehatan ini? Bagaimana jika asuransi menggunakan data wearable untuk menolak klaim? Di Uni Eropa, GDPR melarang penggunaan data kesehatan tanpa persetujuan eksplisit, sementara di Indonesia regulasinya masih ambigu. Selain itu, masalah aksesibilitas—harga wearable canggih (Rp5-15 juta) menjadikannya barang mewah bagi sebagian besar masyarakat. Wearable adalah revolusi kesehatan preventif, tapi tanpa regulasi protektif dan harga terjangkau, teknologi ini justru bisa menciptakan ketimpangan kesehatan digital.
Edge Computing: Otak Terdistribusi di Era IoT
Jika cloud computing adalah "otak pusat", maka edge computing adalah "saraf tepi" yang memproses data dekat dengan sumbernya. Teknologi ini krusial untuk IoT dan 5G karena mengurangi latensi hingga 90% dan menghemat bandwidth. Contoh nyata: di pabrik industri 4.0, sensor mesin memproses data secara lokal di edge server untuk deteksi kerusakan real-time tanpa harus mengirim data ke cloud. Di Jakarta, Transjakarta mengimplementasikan edge computing untuk sistem pemantauan armada bus—data GPS dan kondisi mesin dianalisis di kendaraan itu sendiri, baru hasilnya dikirim ke pusat.
Keunggulan edge computing terbukti dalam krisis: saat gempa Cianjur 2022, jaringan cloud terputus, tapi sistem early warning berbasis edge tetap beroperasi karena tidak bergantung pada koneksi pusat. Namun, implementasinya kompleks: membutuhkan infrastruktur server terdistribusi, keamanan data di setiap titik, dan tenaga ahli yang masih langka di Indonesia. Perusahaan seperti TelkomSigma mulai menawarkan layanan "Edge as a Service", tapi biayanya masih tinggi bagi UMKM. Edge computing adalah fondasi tak terlihat dari smart city dan industri masa depan, tapi pemerataan akses dan keamanan data menjadi PR besar.
Keamanan Siber: Perang Bayangan di Ruang Digital
Seiring digitalisasi, ancaman siber berkembang pesat—dari serangan ransomware hingga cyber espionage. Data BSSN menunjukkan serangan siber di Indonesia meningkat 375% selama 2020-2023, dengan target utama sektor keuangan, kesehatan, dan infrastruktur kritis. Teknologi keamanan pun berevolusi: AI-driven security (seperti Darktrace) mendeteksi anomali jaringan secara real-time, sementara Zero Trust Architecture menggantikan model "kepercayaan lalu verifikasi" dengan "never trust, always verify".
Tapi permasalahan fundamental tetap: kurangnya sumber daya manusia. Indonesia hanya memiliki 15.000 profesional siber dari kebutuhan 100.000. Serangan terhadap Bank Jateng (2022) dan BPJS Kesehatan (2021) membuktikan betapa rentannya sistem kita. Di sisi lain, teknologi seperti quantum key distribution (QKD) menawarkan enkripsi "tidak bisa dibobol" dengan prinsip fisika kuantum, tapi implementasinya masih mahal dan terbatas. Keamanan siber bukan lagi masalah teknis semata, tapi pertahanan nasional. Tanpa investasi serius dalam SDM dan infrastruktur, Indonesia bisa menjadi "siber colony" bagi negara lain.
Menjadi Arsitek Masa Depan di Tengah Badai Teknologi
Teknologi bukan lagi gelombang yang bisa ditahan—ia adalah tsunami digital yang mengubah segala aspek kehidupan, dari cara kita bangun tidur hingga cara kita memaknai eksistensi. Melalui 15 poin yang telah diurai, satu kebenaran fundamental muncul: kemajuan teknologi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka pintu paradoks—kecerdasan buatan yang mendiagnosis kanker dengan akurasi 95% sekaligus mengancam privasi; IoT yang menciptakan kota pintar sekaligus membuka peluang serangan siber; blockchain yang mendemokratisasi keuangan sekaligus menjadi sarana kejahatan. Di sisi lain, teknologi juga adalah jawaban atas krisis eksistensial manusia: teknologi hijau melawan perubahan iklim, quantum computing mempercepat penemuan obat, dan wearable memperpanjang usia produktif.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi digital terbesar di Asia Tenggara, berada di titik krusial. Kita memiliki modal berharga: 191 juta pengguna internet yang haus inovasi, ekosistem startup yang dinamis (Gojek, Traveloka, Bukalapak), dan sumber daya alam yang mendukung teknologi hijau. Namun, kita juga dihadap pada jurang digital yang menganga: 12.000 desa belum terjangkau internet, 23 juta pekerja terancam otomatisasi, dan hanya 15.000 profesional siber dari kebutuhan 100.000. Tanpa strategi yang holistik, teknologi justru akan memperdalam ketimpangan—bukan hanya ekonomi, tapi juga akses kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial.
Untuk itu, tiga pilar menjadi kewajiban kolektif:
- Regulasi yang Cerdas dan Adaptif:
UU Perlindungan Data Pribadi dan draft RUU Kecerdasan Buatan harus diimplementasikan dengan tegas, bukan sekadar di atas kertas. Badan pengawas teknologi independen perlu dibentuk untuk mengawasi etika AI, keamanan IoT, dan praktik platform media sosial.
- Investasi pada SDM Teknologi:
Program seperti "Digital Talent Scholarship" harus diperluas ke pelosok negeri, sementara kurikulum pendidikan wajib dirombak untuk memasukkan literasi koding, keamanan siber, dan etika digital sejak SD.
- Inovasi yang Berpijak pada Kebutuhan Lokal:
Teknologi harus menjawab masalah spesifik Indonesia—dari sensor IoT untuk pertanian lahan kering hingga AI yang memahami bahasa daerah. Startup dan pemerintah harus kolaborasi menciptakan solusi "dari Indonesia, untuk Indonesia".
Revolusi teknologi bukanlah pilihan—ia adalah keniscayaan. Pertanyaannya bukan apakah kita akan terdampak, tapi bagaimana kita memanfaatkannya. Seperti palu godok di tangan pandai besi, teknologi adalah alat yang bisa memahat masa depan yang lebih baik atau menghancurkan fondasi peradaban. Di era di mana kode pemrograman lebih berkuasa dari undang-undang, menjadi pilot teknologi bukanlah kemewahan—melainkan kewajiban moral.
Maka, mari kita jadikan Indonesia bukan sekadar pasar teknologi global, tapi gudang inovator yang mengubah dunia. Dari Sabang hingga Merauke, dari desa terpencil hingga pusat startup, teknologi harus menjadi jembatan menuju Indonesia yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaulat. Karena pada akhirnya, masa depan bukan sesuatu yang ditunggu—melainkan sesuatu yang kita ciptakan, satu baris kode, satu sensor IoT, dan satu terobosan inovasi pada satu waktu.
Credit
1. Photo by Javier Quesada on Unsplash, via https://unsplash.com/s/photos/technology, (Under License : Unsplash License free to use).
2. Photo by Alex Knight on Unsplash, via https://unsplash.com/s/photos/technology, (Under License : Unsplash License free to use).
Categories: Technology
Tags: #Programming #Technology #Self Reminder #Science #Petualangan


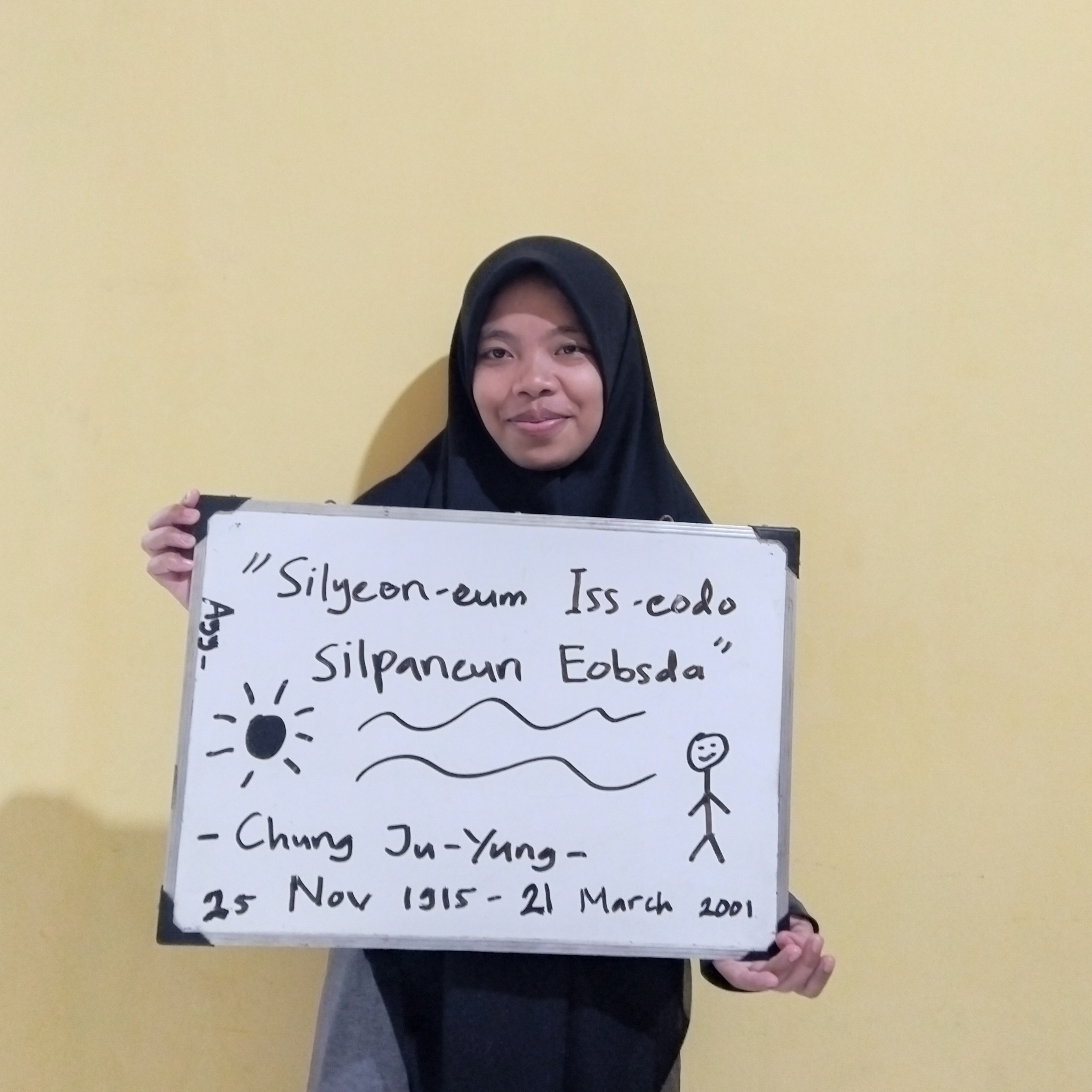



0 Comments
Leave a comment